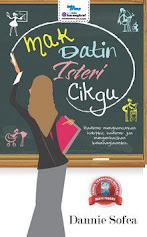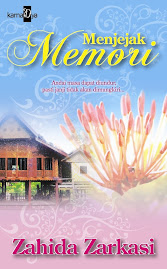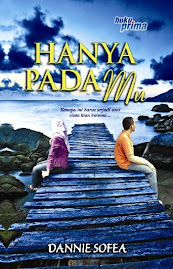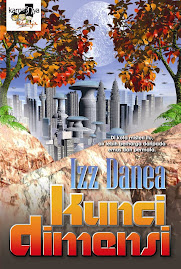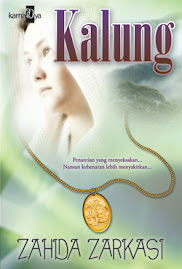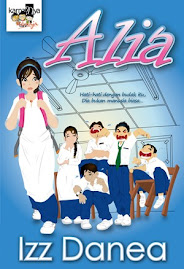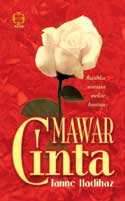BAB 2
“Nah tetap tak setuju!”
“Takkanlah abang nak halau mereka Nah. Ke mana mereka
nak pergi lagi kalau abang halau mereka?”
“Ke rumah mak bapak merekalah! Mereka bukannya anak yatim piatu. Mereka
masih ada orang tua!”
“Kan Nia dah bagitahu yang Yah mintak mereka ke sini.
Yah dan suaminya akan menyusul kemudian.”
“Mula-mula dua orang datang. Lepas ni dua orang lagi.
Jenuhlah kalau macam ni bang. Rumah kita bukannya besar. Dah le nak makan pun
tak cukup! Nah tak kira, abang kena suruh budak dua orang tu keluar segera esok
pagi dari rumah kita ni.”
“Nah… nak keluar dari sini bukannya mudah.”
“Macam mana mereka nak keluar dari sini tu masalah
mereka bang. Bukan masalah kita. Tapi sebaliknya kalau mereka terus tinggal
sini, itulah masalahnya. Selama ni kita bertiga pun tak cukup, ini nak tambah
dua lagi! Teruklah kalau macam ni!”
“Mereka duduk sini sementara saja Nah. Bila Yah dengan
suaminya menyusul nanti mereka akan pergi. Nah kena bersabar. Mereka tu bukan
orang lain. Anak saudara kita juga.”
“Anak saudara abang sorang saja tau! Bukan anak saudara
Nah! Nah tak nak bertanggungjawab kalau sesuatu berlaku pada mereka!”
Malam itu aku terdengar perbalahan mulut antara Pak Long
dan isterinya dari bilik sebelah. Kehadiran aku dengan Irfan yang tak diundang
rupa-rupanya tidak disenangi oleh Mak Long. Kalaulah aku tidak berjanji pada
ibu untuk menunggu kehadirannya, pasti saat ini juga aku mengajak Irfan untuk
meninggalkan rumah Pak Long segera. Aku tidak mahu perbalahan Pak Long dan Mak
Long berlanjutan.
Irfan sudah dibuai mimpi saat aku terdengar perbalahan
Pak Long dan Mak Long. Irfan asyik merungut sejak tiba di rumah Pak Long.
Televisyen tak ada, radio pun tak ada. Bilik air pula di luar. Aku hanya mampu
meminta Irfan supaya bersabar untuk sedikit hari lagi. Bila ibu sudah datang,
kami akan kembali ke bandar.
Setelah tidak terdengar lagi perbalahan dari bilik
sebelah, aku lantas menarik bantal yang diserahkan Pak Long kepadaku sebelum
aku masuk bilik. Bantal tersebut tidak bersarung. Bau hapak menusuk ke hidung. Aku
menepuk-nepuk bantal tersebut untuk membuang habuk yang melekat. Aku tidur di
tengah-tengah antara Irfan dan nenek.
Nenek sedang terbaring lena. Mukanya berkedut seribu.
Aku tidak menyangka dapat berkenalan dengan nenek. Ibu juga tidak pernah
menyebut tentang nenek sehingga aku menyangkakan yang aku tidak mempunyai nenek
sebelah ibu. Sayangnya ingatan nenek sudah pudar. Banyak yang nenek sudah tidak
ingat. Penglihatannya juga lemah.
Kesejukan mencengkam sehingga ke tulang. Aku membuka beg
pakaian lalu mengeluarkan kain batik untuk dijadikan selimut. Malam itu aku
tidur dengan lena kerana terlalu letih.
* * * * * *
Pertengahan Februari….
“Kak!”
Aku terpinga!
Segera aku toleh ke belakang. Irfan tersengih-sengih, menayang dua batang gigi
kapaknya yang baru tumbuh.
“Fan nak kakak mati
ke?” kus semangatku diterjah Irfan dari belakang. Sudahlah aku waktu itu sedang
asyik melayan perasaan sambil mengamati banglo biru di puncak bukit dengan
khayalan yang pelbagai memenuhi ruang kotak imaginasiku.
“Kakak janganlah
cakap macam tu… Fan tak nak duduk sorang….”
Muka Irfan berubah muram. Irfan baru balik dari sekolah
kerana menghadiri aktiviti kokurikulum. Setelah seminggu berada di kampung,
akhirnya aku mendaftar nama Irfan di sekolah rendah berhampiran. Itulah pesanan
ibu, supaya aku mendaftar Irfan di sekolah berhampiran sebaik sahaja tiba di
kampung. Seminggu berlalu barulah aku mendaftar nama Irfan. Aku sengaja tunggu
kedatangan ibu dan abah yang berjanji hendak menyusul. Setelah seminggu, ibu
dan abah masih tidak kelihatan batang hidup mereka. Aku terpaksa mendaftar
Irfan di sekolah rendah berhampiran. Kelas Irfan hanya ada 12 orang pelajar
sahaja.
“Lain kali jangan
kejutkan kakak macam tu lagi.” Aku memberi peringatan. Aku memang tidak suka
dikejutkan dari arah belakang. Semangatku lemah.
“Maafkan Fan….
Kakak termenung apa tadi sampai Fan datang pun kakak tak sedar? Kakak
teringatkan ibu dengan abah ke?” aju Irfan. “Fan pun selalu ingatkan mereka.
Bila ibu dengan abah nak datang kak? Fan dah penat menunggu. Dah lebih sebulan
kita di sini… tapi ibu dengan abah tak muncul-muncul juga.” Rungut Irfan.
Orang tuaku masih
belum muncul seperti yang dijanjikan mereka. Setiap detik aku teringatkan
mereka. Namun aku enggan luahkan pada Irfan. Aku tidak mahu fikiran Irfan
terganggu. Aku sendiri sebenarnya tidak dapat memberi jawapan kepada Irfan.
Walaupun kepalaku hampir pecah memikirkan mengapa aku dan Irfan dipaksa pulang
ke kampung, jawapan munasabah masih belum juga ditemui.
Tak mungkin ibu dan
abah tidak sanggup lagi menjaga aku dan Irfan… Kalau ibu dan abah tak sanggup
memikul tanggungjawab, tentu sejak kecil lagi aku, Irfan dan kakak telah
dibuang. Tetapi kami dibelai dan dijaga sehingga besar. Kalau ibu dan abah tak
sanggup memikul beban, tentu aku dipaksa berhenti belajar dan mencari kerja
bagi meringankan beban mereka. Namun sebaliknya pula yang berlaku. Selepas
tamat STPM, aku mahu mencari kerja tetapi ibu berkeras menghalang. Aku dipujuk
ibu meneruskan pelajaran di kolej kerana gagal menempatkan diri di universiti
seperti teman-temanku yang lain. Kakak bersetuju dengan pendapat ibu. Kakak
berjanji hendak menyaraku.
“Kak… Fan rindu
ibu… abah…..”
“Kakak teringin nak pergi ke banglo besar atas bukit
tu.” Aku menukar tajuk perbualan, bimbang air mata menitis. Mataku tertancap
pada sebuah banglo yang dicat warna biru. Banglo tersebut dibina di atas salah
sebuah bukit yang mengelilingi Kampung Jerai Tua. Tiada rumah lain yang
kelihatan berhampiran banglo tersebut. Siapakah pemilik banglo tersebut?
Tentunya dia bukan calang-calang orang. Tentunya dia seorang yang berpengaruh
di kampung ini. Kediamannya jauh beza dengan kediaman Pak Long dan penduduk
Kampung Jerai Tua yang lain.
“Jangan kak!”
halang Irfan. “Mael cakap banglo tu berhantu! Tak ada sesiapa yang berani ke sana sana
Berhantu? Aku
tersenyum dan menggeleng. Terasa lucu mendengar bicara Irfan. “Mana ada hantu
zaman sekarang… Fan.” Aku tidak mahu Irfan terpengaruh dengan cerita karut dari
teman sekolahnya. Bukan setakat budak-budak, penduduk kampung pun ramai yang
masih percaya dengan cerita tahyul. Sejak menjejakkan kaki ke kampung tersebut,
aku sudah dapat merasa sikap sebahagian penduduk kampung yang agak pelik.
Mereka terlalu percayakan cerita karut-marut. Sentiasa ada hantu syaitan
melingkari hidup mereka. Jadi, apa yang hendak dilakukan mereka harus ada jampi
serapah atau memakai tangkal pendinding.
Aku yakin banglo
tersebut berpenghuni. Lampu sentiasa menyinari banglo tersebut pada malam hari.
Bererti banglo tersebut memang berpenghuni. Siapakah pemilik banglo tersebut?
Kenapa banglo tersebut dikatakan berhantu sedangkan ada penghuni yang tinggal
di dalamnya? Jika berhantu tentu tidak ada yang berani tinggal di situ. Aku
teringin ke situ untuk melihat banglo tersebut dari jarak dekat namun aku tidak
tahu jalan manakah yang harus kulalui. Nampak seperti tiada jalan ke banglo
tersebut!
Ingin kuajukan
misteri banglo tersebut kepada seseorang, tapi tidak tahu siapa yang harus
diajukan pertanyaan tersebut. Aku masih belum mengenali lebih rapat penduduk
kampung itu. Yang aku kenal hanyalah dua tiga orang jiran Pak Long. Jika aku
membuka mulut mengenai banglo tersebut, air muka orang yang diaju pertanyaan
akan berubah. Jelas tergambar kebencian di wajah mereka.
Nak ajukan pertanyaan pada Mak Long, jangan harap! Mak
Long tak ingin berbual denganku apatah lagi tentang topik tersebut. Mak Long
memang tak suka padaku dan juga Irfan. Mak Long hanya tahu mengarahkan aku buat
itu ini sahaja. Nak ukir senyum pun susah! Marah benar Mak Long kerana suaminya
bersetuju untuk membenarkan kami menetap sementara di rumahnya. Kalau aku sahaja
yang menjadi sasaran kemarahan Mak Long, aku tak peduli sangat. Malangnya,
Irfan yang belum mengerti apa-apa juga dihentam Mak Long.
“Fan… kenapa tak
balik lagi?” tegurku apabila melihat Irfan masih tak berganjak. Irfan sedang
leka merenung arus sungai. Asyik sekali! Di bandar, tiada sungai sejernih air
sungai di sini. Sungai di bandar sudah tercemar. Ia menjadi tempat pengumpulan
sampah sarap sehingga airnya bertukar keruh dan berbau hanyir.
Sejak tinggal di sini, setiap hari Irfan pasti akan
mandi di sungai terutamanya selepas balik sekolah. Air sungai masih belum
tercemar. Ikan-ikan yang berenang boleh dilihat dengan jelas. Betapa jernihnya
air di sini. Satu sikap orang kampung yang harus dipuji adalah mereka tidak
sanggup hendak mencemarkan sungai di kampung mereka dengan sampah sarap. Selain
menjadi tempat kanak-kanak bermandi-manda, sungai tersebut juga menjadi tempat
orang kampung mencuci pakaian.
Irfan menggeleng.
“Fan nak balik dengan kakak,” ujarnya tanpa memandang wajahku. Benarkah Irfan
sedang menikmati keindahan sungai? Atau Irfan sebenarnya sedang terkenangkan
ibu dan abah?
“Kakak nak duduk
lama sikit, Fan.” Aku mahu mencari ketenangan di situ. Biarpun ketenangan
sementara…. Badanku letih membuat kerja rumah sejak awal pagi. Setelah selesai melipat
kain, barulah aku melangkah keluar dari rumah. Ketika aku meninggalkan rumah,
Mak Long yang sentiasa mengawal gerak-geriku tiada di rumah. Aku juga perlukan
rehat secukupnya. Jika asyik didera dengan membuat macam-macam kerja mungkin
lama-kelamaan aku akan jatuh sakit. Jika aku jatuh sakit, tak ada sesiapa lagi
yang akan menjaga Irfan. Sebab itu aku curi-curi keluar untuk menghirup udara
segar.
Aku sudah maklum jadual harian Mak Long. Dia bangun pagi
selepas angka sembilan. Selepas mencuci muka, dia akan mengisi perut. Jika ada
yang tidak kena dengan sarapan yang aku buat, mulalah dia mengomel. Dituduhnya
orang bandar seperti aku langsung tak pandai memasak. Masinlah, tawarlah dan
macam-macam lagi komen yang diberinya. Yang peliknya, kuih atau jemput-jemput
yang aku hidangkan padanya tak pernah tak habis walaupun tak sedap!
Selepas perut kenyang, Mak Long akan keluar. Ke mana,
aku belum pasti. Yang pasti, dia bukan keluar bekerja. Tengah hari Mak Long
akan balik untuk makan. Seperti biasa, ketika sedang menjamu selera, dia akan
komen itu ini akan masakan yang aku sediakan. Kemudian Mak Long akan tidur.
Sebelah petang Mak Long akan keluar lagi sehingga waktu Maghrib. Entah ke
manalah Mak Long menghabiskan masanya.
“Kalau macam tu, Fan akan temankan kakak.”
“Fan dah siapkan
kerja sekolah?” aku tidak mahu Irfan lama-lama di situ. Nanti semua kerja
sekolah tak sempat disiapkannya. Aku mahu dia menyiapkan semua kerja sekolahnya
sebelum hari gelap. Irfan tentu tidak selesa andai terpaksa menyiapkan kerja sekolahnya
di sebelah malam dengan cahaya dari pelita ayan. Lagi pula, pelita ayan hanya
ada tiga biji sahaja. Mak Long akan merepek sakan andai Irfan menggunakan
pelita ayan untuk menyiapkan kerja sekolah.
Irfan menggeleng.
Keras betul hatinya.
“Fan?” aku tidak
mahu Irfan menjadi pemalas. Hanya pelajaran sahaja yang dapat mengubah
kehidupannya suatu hari nanti. Nak harapkan harta warisan orang tua, tak
usahlah bermimpi. Ibu dan abah tak punya harta walau seutas rantai emas pun.
“Fan tak tahan kak.
Mak Long asyik membebel aje. Itu tak kena! Ini tak kena!” luah Irfan setelah
terdiam seketika. Tergambar kebencian di wajahnya ketika menyebut nama Mak
Long.
“Mak Long tak ada
di rumah sekarang. Kan
Entah ke manalah aku dan Irfan hendak melangkah pergi.
Hendak pulang ke bandar, aku sudah tidak punya duit. Dan jika mahu keluar dari
kampung juga, bukannya mudah. Perlu minta orang kampung untuk menghantar ke
pekan. Itu pun jika ada orang kampung yang sudi membantu. Sudah sampai ke
pekan, aku harus menumpang teksi pula untuk ke Pekan Manggis. Hanya di Pekan
Manggis, perkhidmatan bas ekspres disediakan. Jaraknya bukan dekat dan
tambangnya juga bukan murah.
“Telinga Fan
bukannya pekak, kakak. Fan tak tahan lagi tinggal di rumah Mak Long.”
“Dah, dah....” Aku
membelai mesra Irfan. Aku simpati padanya. Dalam usia semuda itu, Irfan telah
melalui pelbagai dugaan. Paling aku bimbang, mampukah Irfan menempuhi segala
dugaan tersebut. Aku sendiri pun hampir mengalah apa lagi Irfan. Telingaku juga
panas setiap kali mendengar cacian Mak Long. Ingin melawan, bimbang aku dan
Irfan dihalau. Mak Long memperlakukan aku seperti hamba abdi. Sedangkan dia
hanya goyang kaki. Dia sengaja mengambil kesempatan ke atasku. Dipaksanya aku
buat kerja itu ini kerana menumpang di rumahnya secara percuma.
“Kita balik ke
bandar kak. Fan tak suka tinggal di sini.” Luah Irfan. “Fan rindukan abah dan
ibu. Fan juga rindukan teman-teman sekolah lama. Mereka semua baik. Tak seperti
teman sekolah di sini. Mereka hanya tahu membuli Irfan kalau Irfan tak mengikut
cakap mereka.”
“Fan, Fan lupa ke
pesan abah dengan ibu? Abah dengan ibu yang suruh kita ke sini. Tentu ada
sebabnya mereka minta kita ke sini, kan
“Ibu janji nak datang dengan abah. Kenapa tak
datang-datang lagi? Fan dah bosan tinggal sini. Fan nak balik. Fan tak suka
tinggal di sini, kak….” Rengek Irfan.
“Ibu dengan abah dah janji. Pasti ibu dan abah akan
datang. Fan jangan bimbang. Kita tunggu saja.” Aku cuba
Ibu tidak pernah menceritakan tentang kampung
halamannya. Ini membuatkan aku menyangka yang ibu orang bandar yang tidak berkeluarga.
Dan aku sangkakan kisah hidup ibu sama seperti abah. Abah dari tanah seberang,
datang ke Malaysia
BAB 3
Awal Mac….
Aku
melangkah anak tangga kayu satu demi satu. Anak tangga kayu itu yang hampir
reput menuntut aku untuk lebih berhati-hati. Mahu minta Pak Long gantikan kayu
tersebut, bimbang nanti dituduh mengada-ngada pula.
“Abang
oi, kita nak makan apa malam ni? Beras dah habis.”
Baru
sebelah kakiku melangkah ke beranda, terdengar laungan lantang Mak Long dari
arah dapur. Pak Long yang sedang menggulung rokok daun di beranda bingkas
bangun. Rokok diselit celah bibir. Pemetik api dihidupkan lalu diacukan ke
hujung rokok daun. Muka Pak Long tampak tak bermaya. Aku bimbang akan
kesihatannya yang mungkis terjejas kerana terpaksa bekerja lebih keras sejak
kedatangan aku dan Irfan.
“Abang
ni tak dengar ke apa Nah cakap?” tengking Mak Long yang sudah tercegat di muka
pintu. Dia bercekak pinggang, bergaya seperti seorang boss.
“Abang
dengar... abang nak pergi beli ni,” jawab Pak Long malas sambil menggulung kain
pelikat yang hampir londeh.
“Ayam
belakang rumah tu siapa nak bagi makan? Dah nak masuk Maghrib ni, ayam tak bagi
makan lagi!” rungut Mak Long sambil menjeling ke arahku.
“Biar
Nia pergi beli beras.” Aku mempelawa diri. Memang itulah tujuan sebenar Mak
Long, mahu menyuruh aku ke kedai untuk membeli beras. Mak Long memang tak suka
kalau melihat aku dalam keadaan tidak bekerja. Setiap minit kena ada kerja yang
aku lakukan. Mak Long menganggap aku dan Irfan seperti bala yang datang untuk
menambahkan kesengsaraan keluarganya yang dihimpit kemiskinan.
Pak
Long membuka beg tembakaunya lalu mengeluarkan not sepuluh ringgit. “Beli tiga kilo beras.” Pak Long menghulurkan
duit kepadaku.
Aku
mengambil duit yang dihulurkan Pak Long. Duit yang lembap dan berbau tembakau
itu menusuk hidungku. Aromanya menyesak nafasku.
“Dulu,
tiga kilo cukup untuk seminggu. Sekarang ni hanya dua tiga hari je. Jenuh le
kalau macam ni setiap hari!” sindir Mak Long.
Aku
terus melangkah menuruni anak tangga. Apa yang dicakapkan Mak Long memang
betul. Kedatangan aku dan Irfan hanya membebankan keluargnya. Pendapatan Pak
Long tidak seberapa. Pak Long penoreh getah. Jadi, pendapatan Pak Long ikut
keadaan cuaca. Jika kemarau, banyaklah sikit pendapatannya. Namun terpaksa
dibahagi dua dengan majikan kerana kebun getah bukan milik Pak Long. Pak Long
hanya kuli. Mak Long pula tidak bekerja.
“Kakak
nak pergi mana?” Irfan tercegat di kaki tangga dalam keadaan resah. Dia memang
tidak suka jika aku keluar. Irfan merasakan yang keselamatannya tidak terjamin.
“Kedai...
nak beli beras.” Aku menyarung selipar buruk. Aku harus segera berangkat ke
kedai kerana jam sudah menghampiri angka tujuh.
“Nak
ikut!” muka Irfan penuh mengharap.
“Tak
boleh Fan. Dah nak Maghrib ni. Fan pergi mandi lepas tu solat.” Aku tidak mahu
Irfan kehabisan tenaga berjalan jauh. Bukannya dekat kedai runcit Pak Malik.
Aku bimbang tenaga Irfan habis di tengah jalan. Hendak ke kedai Pak Malik, aku
terpaksa menyeberang sungai dan mengikut jalan tanah merah. Kedainya terletak
di sebelah hulu sungai.
“Tak
nak! Fan nak ikut kakak.” Irfan separuh merengek, mengharap agar lakonannya itu
berjaya memujukku.
“Jauh
Fan. Nanti Fan penat. Kerja sekolah tak sempat nak siapkan nanti.” Aku tetap
takkan membenarkan Irfan mengekoriku. Aku bukannya hendak berlama-lama di
kedai, tetapi sekadar untuk membeli beras.
Irfan
menarik muka masam. Aku terus menapak agar segera sampai ke kedai sebelum malam
menjengah. Aku terpaksa berjalan hampir dua puluh minit, melalui denai,
jambatan kayu dan ke jalan besar tanah merah. Untuk ke kedai runcit, aku harus
berjalan jauh ke hulu. Itulah salah satu kedai runcit paling besar yang
terdapat di Kampung Jerai Tua. Malangnya tak semua barang ada di kedai Pak
Malik. Kalau hendak membeli lima jenis barang, pasti sekurang-kurangnya satu
telah kehabisan.
Otakku
ligat memikir cara untuk mendapatkan pendapatan. Sedikit pun jadilah asalkan
dapat meringankan beban Pak Long. Ibu dan abah belum tentu datang. Aku tidak
mahu mengharap lagi. Aku dan Irfan sengaja dilemparkan ke kampung tersebut kerana
ibu dan abah tidak sanggup lagi menanggung kami berdua... sekurang-kurangnya
itulah yang bermain di mindaku saat itu. Aku tak dapat memikirkan sebab lain
lagi!
Aku tidak boleh bergantung
hidup pada rezeki Pak Long semata-mata. Sudah hampir dua bulan aku dan Irfan
tinggal di rumah Pak Long. Sesen pun aku masih belum hulurkan pada Pak Long.
Wang yang diberi ibu memang tidak cukup. Aku terpaksa berhutang dengan Pak Long
untuk membayar yuran persekolahan Irfan. Aku berjanji akan menjelaskannya
apabila ibu dan abah datang. Mujurlah Pak Long jenis lelaki yang tidak kisah.
Hanya Mak Long yang kurang senang apabila aku meminjam wang suaminya. Dia
mendesak aku supaya membayar segera.
Selain Mak Long, Pak Long
terpaksa menanggung nenek. Nenek sudah nyanyuk. Kencing dan berak merata-rata.
Tidur tak tentu waktu. Sejak ketibaanku ke rumah Pak Long, akulah yang
mengambil alih tugas Mak Long menjaga nenek. Kerja yang tidak pernah terfikir
akan kulalui. Pertama kali melihat nenek, aku terkejut. Ibu tidak pernah menyebut
langsung tentang Nek Esah, sedangkan wanita itulah yang telah membesarkan ibu.
Tak seharusnya ibu melupakan nenek begitu saja....
Ketika
sedang mengelamun itulah, tiba-tiba sebuah pacuan empat roda bergerak terus ke
arahku. Aku sedang melintas jalan pada masa itu. Kerana terlalu kaget, aku
terus kaku di tengah jalan. Lututku menggeletar. Pacuan empat roda berhenti
betul-betul di hadapanku! Berdecit bunyi tayar menekan tanah merah yang berbatu
kerikil itu. Aku nyaris dilanggar. Jantung berdegup kencang. Pemandu Pajero
dengan wajah serius merenung tajam ke arahku seolah-olah mahu menelan. Aku
bergerak ke tepi menyedari yang aku sedang menghalang perjalanannya.
“Maaf!”
Hanya perkataan maaf yang keluar dari bibirku. Memang aku yang bersalah. Aku
tidak menoleh kiri dan kanan terlebih dulu sebelum melintas kerana pada
anggapanku, jalan tersebut tidak sibuk dengan kenderaan yang lalu lalang. Peluh di dahi aku kesat dengan lengan baju.
Mujurlah pemandu tersebut tidak turun dan memarahiku. Dia hanya merenungku tajam
dari dalam kereta. Sebentar kemudian, pacuan empat roda terus meluncur laju,
menerbangkan debu sepanjang jalan. Aku segera menekup muka, menghalang debu
mengotori muka. Laju benar Pajero itu dipandu.
Syukur ke hadrat Ilahi kerana
aku tidak mengalami sebarang kecederaan. Aku mengurut dada kelegaan. Persoalan
menerjah ke fikiranku tentang pemilik pacuan empat roda tersebut. Setahuku,
majoriti penduduk kampung tersebut hanya bekerja sebagai penoreh getah.
Selebihnya berniaga kedai runcit, kedai kopi, tukang rumah dan membuka kedai
memungut getah. Tak mungkin mereka mampu menggunakan pacuan empat roda walaupun
hanya kereta tersebutlah yang paling sesuai digunakan di jalan kampung yang
tidak bertar dan berbukit-bukau itu.
Aku
melangkah ke kedai runcit Pak Malik yang terletak di depan mata dengan
persoalan yang masih berlegar di kepala. ‘Siapakah lelaki yang memandu Pajero
itu?’
“Tak
apa-apa ke?” soal Pak Malik yang turut menyaksikan kejadian yang hampir
menimpaku di hadapan kedainya itu.
“Tak,
saya okey. Er... siapa pemandu Pajero tu?” aku terus ajukan persoalan yang
bermain di fikiran. Yang ada dalam fikiranku saat itu, lelaki tersebut adalah
orang luar. Pak Malik mungkin mengenali
lelaki tersebut.
Pak
Malik memandang sekeliling. “Itulah pembunuh sakit jiwa,” bisik Pak Malik
setelah yakin tiada sesiapa yang mencuri dengan kata-katanya itu.
“Pembunuh?”
aku melopong. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku amati wajah Pak Malik,
mengharapkan penjelasan.
Pak
Malik memberi isyarat agar aku memperlahankan suara.
“Baru
keluar penjara?” aku hairan kerana lelaki itu tampak masih muda. Kalau sudah
dijatuhi hukuman kerana membunuh, tentu dia dikenakan hukuman mati mandatori
atau sekurang-kurangnya meringkuk dalam penjara seumur hidup. Atau... adakah
dia bersembunyi di sini supaya tidak dikesan pihak polis? Tempat ini memang
sesuai dijadikan kawasan persembunyian.
Pak
Malik menggeleng. Nampak seperti dia gusar dengan pertanyaanku itu. “Kenapa dia....”
“Nak
beli apa?” Pak Malik memintas pertanyaanku tiba-tiba.
“Beras...
3 kilo.” Pak Malik keberatan untuk menceritakan kepadaku lebih lanjut mengenai
pembunuh sakit jiwa yang hampir melanggarku sebentar tadi. Aku agak hampa.
Cerita tentang pembunuh sakit jiwa tersebut menarik perhatianku.
Seorang
lelaki yang hampir sebaya dengan Pak Malik melangkah masuk. “Aku nak beli
barang-barang ni.” Dia menghulurkan cebisan kertas kepada Pak Malik. Matanya
tiba-tiba merenung ke arahku. Aku hadiahkan senyuman namun tak dibalas lelaki
berjambang tebal itu. Aku tarik balik senyuman. Mukanya sentiasa bengis.
Akhirnya aku mengalah. Aku tidak berani hendak bertentang mata dengannya lagi.
Lelaki itu seperti kurang senang denganku.
“Nah.”
Pak Malik menghulurkan beras yang sudah ditimbang. Aku menghulurkan wang.
Sambil menunggu Pak Malik menyerahkan baki wang, aku perhati gerak-geri lelaki
berjambang putih itu yang sedikit mencurigakan. Aku tak pernah melihat atau
terserempak dengannya sebelum ini. Setiap hari, pasti aku akan berjumpa dengan
muka-muka baru di kampung. Ada yang dapat menerima kehadiranku di kampung
mereka. Tak kurang juga yang memandang serong padaku. Entah apa yang tak kena
pada diriku.
“Balik
cepat. Dah nak Maghrib ni.” Pesan Pak Malik sambil menghulurkan baki wang.
Matanya melirik ke arah lelaki berjambang putih itu. Pak Malik seolah sedang
memberi isyarat padaku yang lelaki tersebut berbahaya.
Aku terpaksa beredar walaupun
hatiku melonjak ingin tahu lebih lanjut mengenai pembunuh sakit jiwa dari mulut
Pak Malik. Senja kian menghampiri. Jalan tanah merah itu aku redah. Hanya pokok
getah dan semak-samun di kiri dan kanan jalan. Selama ini aku hanya melihat di
kaca televisyen sahaja tentang kampung yang masih mundur dan ketinggalan dalam
arus kemajuan. Kini aku menjadi sebahagian penghuni kampung tersebut.
Pembunuh
sakit jiwa masih menghantui kepalaku. Aku menoleh kiri, kanan dan belakang.
Jantungku terus berdegup kencang. Ayunan langkah aku percepatkan. Sesekali aku
menoleh ke belakang untuk memastikan yang aku tak diekori. Manalah tahu jika
pembunuh tersebut mahu membalas dendam kepadaku!
untuk mendapatkan novel KALUNG